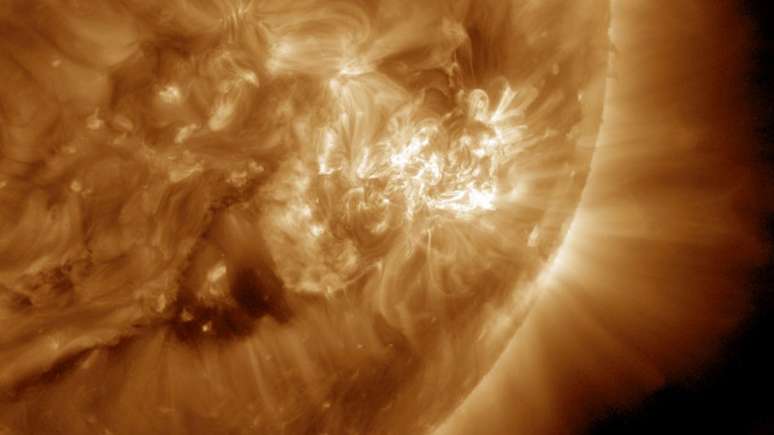Ketika saya masih kuliah, saya membaca “The Sea and Poison,” sebuah novel tahun 1950-an karya Shusaku Endo. Ini menceritakan kisah seorang dokter di Jepang pascaperang yang, saat magang beberapa tahun sebelumnya, berpartisipasi dalam percobaan pembedahan makhluk hidup pada seorang tahanan Amerika. Sudut pandang Endo terhadap cerita ini bukanlah yang termudah, secara etis; dia tidak memikirkan penderitaan korbannya. Sebaliknya, ia memilih untuk mengeksplorasi elemen yang lebih meresahkan: kemanusiaan para pelakunya.
Ketika saya mengatakan “kemanusiaan” yang saya maksud adalah kebingungan mereka, pembenaran diri dan kesediaan mereka untuk membohongi diri mereka sendiri. Kekejaman tidak hanya muncul dari kejahatan, kata Endo, namun muncul dari kepentingan pribadi, sifat takut-takut, sikap apatis, dan keinginan untuk mendapatkan status. Novelnya menunjukkan kepada saya bagaimana, di tengah tekanan sosial yang tepat, saya juga bisa menipu diri sendiri untuk membuat pilihan yang akan menyebabkan terjadinya kekejaman. Mungkin inilah sebabnya mengapa buku ini menghantui saya selama hampir dua dekade, sehingga saya sudah membacanya berkali-kali.
Saya teringat akan novel itu pada jam 2 pagi baru-baru ini ketika saya menelusuri akun media sosial yang didedikasikan untuk mengumpulkan ulasan pembaca yang marah. Perhatian saya tertuju pada seseorang bernama Nathan, yang pendapatnya tentang “Paradise Lost” adalah: “Milton adalah orang fasis.” Namun pembaca lainnya, Ryan, yang menarik perhatian saya dengan tanggapannya terhadap “Rabbit, Run” karya John Updike: “Buku ini membuat saya menentang kebebasan berpendapat.” Dari sana, saya mendapatkan banyak ulasan “Lolita”: Pembaca terkejut, frustrasi, marah. Pria yang menjijikkan! Bagaimana Vladimir Nabokov diizinkan menulis buku ini? Lagi pula, siapa yang membiarkan penulis menulis karakter yang tidak bermoral dan sesat itu?
Saya terkekeh ketika saya menggulir tetapi segera saya sadar. Di sini, di layar saya terdapat gambaran penyakit khas Amerika: yaitu, bahwa kita mempunyai kecenderungan yang mendalam dan berbahaya untuk mengacaukan seni dengan pengajaran moral, dan sebaliknya.
Sebagai seseorang yang lahir di Amerika namun dibesarkan di sejumlah negara lain, saya selalu mendapati kekuatan moralitas Amerika yang tak kenal kompromi sangat memesona dan menakutkan. Terlepas dari pluralitas pengaruh dan kepercayaan kita, karakter nasional kita nampaknya tidak dapat dihindari dipengaruhi oleh hubungan Perjanjian Lama dengan gagasan tentang yang baik dan yang jahat. Konstruksi yang kuat ini meresap ke dalam segala hal, mulai dari kampanye periklanan hingga kampanye politik — dan kini telah tersaring ke dalam, dan menggeser, fungsi karya seni kita.
Mungkin ini karena wacana politik kita setiap hari berubah-ubah antara gila dan menjijikkan dan kita ingin melawan perasaan tidak berdaya dengan menekankan kesederhanaan moral dalam cerita yang kita ceritakan dan terima. Atau mungkin karena banyak pelanggaran yang luput dari perhatian pada generasi sebelumnya — tindakan misogini, rasisme, dan homofobia; penyalahgunaan kekuasaan baik makro maupun mikro – kini diserukan secara langsung. Kita begitu mabuk dengan menyebut penyakit ini secara terbuka sehingga kita mulai beroperasi di bawah kesalahpahaman bahwa mengakui kompleksitas satu sama lain, dalam komunitas kita dan juga dalam seni kita, berarti memaafkan kekejaman satu sama lain.
Ketika saya bekerja dengan penulis muda, saya sering kagum dengan betapa cepatnya sesi umpan balik rekan berubah menjadi proses mengidentifikasi karakter mana yang melakukan atau mengatakan hal-hal yang tidak sensitif. Terkadang para penulis terburu-buru membela karakter tersebut, namun seringkali mereka meminta maaf dengan malu-malu atas titik buta mereka sendiri, dan diskusi beralih ke cara memperbaiki moral dari karya tersebut. Anggapan bahwa nilai-nilai sebuah karakter tidak bisa berupa nilai-nilai penulis maupun inti dari karya tersebut tampaknya semakin mengejutkan — dan cenderung memicu ketidaknyamanan.
Meskipun saya biasanya berbagi pandangan politik progresif dengan murid-murid saya, saya merasa terganggu dengan kepedulian mereka terhadap kebenaran dibandingkan kompleksitas. Mereka tidak ingin terlihat mewakili nilai-nilai yang tidak mereka anut secara pribadi. Hasilnya adalah, di saat dunia kita belum pernah terasa begitu cepat berubah dan membingungkan, cerita kita menjadi lebih sederhana, kurang bernuansa, dan kurang mampu memahami realitas yang kita jalani.
Saya tidak bisa menyalahkan para penulis muda karena percaya bahwa tugas mereka adalah menyampaikan moralitas publik yang sangat benar. Harapan yang sama ini tersaring ke dalam semua mode tempat saya bekerja: novel, teater, TV, dan film. Tuntutan Internet Nathan dan Internet Ryan — dan kegelisahan para peserta didik saya — tidak jauh berbeda dengan tuntutan para penjaga gerbang industri yang bekerja di wilayah tak bertuan antara seni dan uang dan yang tugasnya adalah melucuti cerita tentang apa pun yang bisa menjadi suram secara etis.
Saya telah bekerja di ruang penulis TV di mana “catatan kesukaan” muncul segera setelah karakter kompleks muncul di halaman – terutama ketika karakter tersebut adalah perempuan. Kekhawatiran tentang kesukaannya paling sering merupakan kekhawatiran tentang moralnya: Bisakah dia dianggap sebagai orang yang tidak pilih-pilih? Egois? Agresif? Apakah dia pacar yang buruk atau istri yang buruk? Seberapa cepat dia bisa direhabilitasi menjadi warga negara teladan bagi pemirsa?
TV tidak sendirian dalam hal ini. Seorang sutradara yang bekerja dengan saya baru-baru ini mengajukan skenario kami ke studio. Ketika para eksekutif lewat, mereka memberi tahu tim kami bahwa itu karena karakternya terlalu ambigu secara moral dan mereka ditugaskan untuk mencari materi yang pelajarannya jelas, agar tidak meresahkan basis pelanggan mereka. Apa yang tidak mereka katakan, namun tidak perlu mereka katakan, adalah bahwa dengan tidak adanya pendanaan seni federal yang memadai, seni Amerika terikat pada pasar. Uang sangat terbatas, dan banyak perusahaan tidak mau membayar untuk cerita yang mungkin akan ditolak oleh pemirsa jika mereka dapat membeli sesuatu yang tidak terlalu penting dalam latar belakang kehidupan kita.
Namun apa yang ditawarkan seni kepada kita sangatlah penting karena seni bukanlah latar belakang yang hambar atau platform untuk arahan sederhana. Buku, drama, film, dan acara TV dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita jika buku-buku tersebut tidak berfungsi sebagai pedoman moral, namun memungkinkan kita untuk melihat sekilas kapasitas tersembunyi kita, kontrak sosial yang licin di mana kita berfungsi, dan kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam diri kita. .
Kita memerlukan lebih banyak narasi yang memberi tahu kita kebenaran tentang betapa kompleksnya dunia kita. Kita membutuhkan cerita yang membantu kita menyebutkan dan menerima paradoks, bukan cerita yang menghapus atau mengabaikannya. Bagaimanapun juga, pengalaman kita hidup dalam komunitas satu sama lain sering kali jauh lebih cair dan mudah berubah dibandingkan hanya sekedar hitam dan putih. Kita mempunyai khalayak yang kita kembangkan, dan semakin kita memupuk khalayak yang percaya bahwa tugas seni adalah memberi instruksi, bukan menyelidiki, menghakimi, bukan bertanya, mencari kejelasan daripada menyimpan banyak ketidakpastian, maka kita akan semakin menemukan diri kita sendiri. dalam budaya yang ditentukan oleh kekakuan, penilaian spontan, dan rasa ingin tahu. Di dunia yang penuh dengan kutukan, perpecahan, dan isolasi, seni – bukan moralisasi – menjadi sangat penting.
Jen Silverman adalah penulis naskah drama dan penulis novel “We Play Ourselves” dan “There Going to Be Trouble.”
The Times berkomitmen untuk menerbitkannya keragaman huruf kepada editor. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang ini atau artikel kami yang mana pun. Ini beberapa tip. Dan inilah email kami: surat@nytimes.com.
Ikuti bagian Opini New York Times di Facebook, Instagram, TIK tok, Ada apa, X Dan benang.