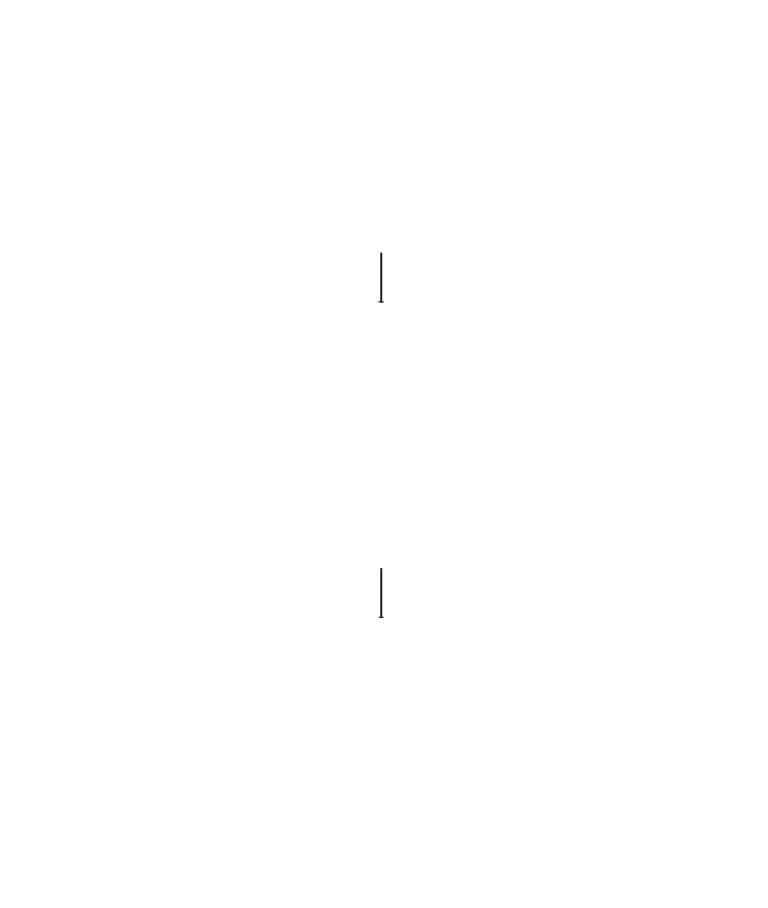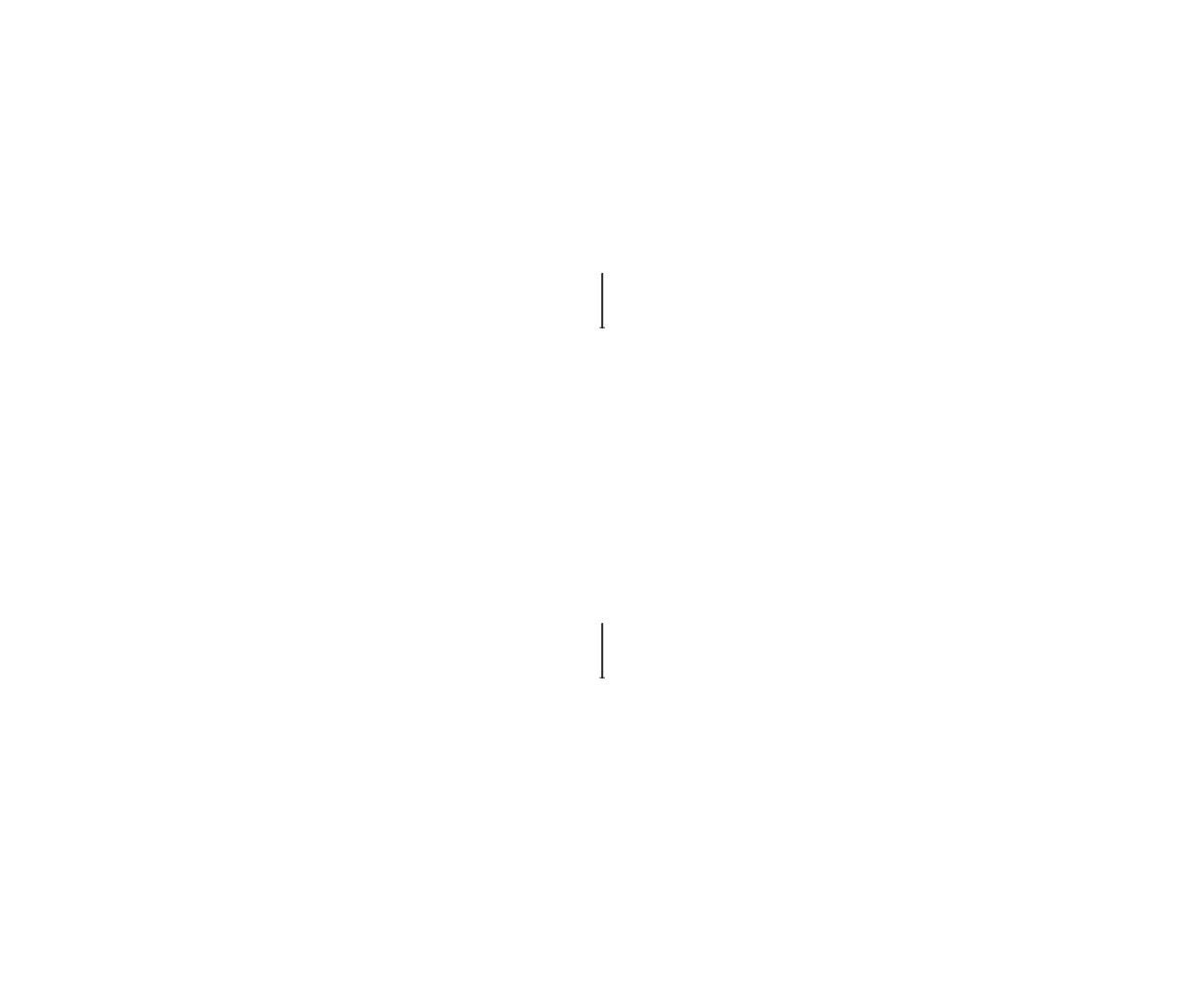Setelah lebih dari enam bulan perang, anak-anak di Jalur Gaza mempunyai banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh orang tua mereka. Kapan pertempuran akan berhenti? Berapa malam lagi mereka akan tidur di lantai? Kapan mereka bisa kembali ke sekolah? Beberapa masih menanyakan teman sekelasnya yang terbunuh.
Orang dewasa tidak tahu harus berkata apa.
Mereka merasa tidak berdaya, putus asa dan kelelahan, kata mereka – lelah karena tantangan merawat luka yang terlihat dan luka yang coba disembunyikan oleh anak-anak mereka.
Untuk melaporkan kisah ini, jurnalis Washington Post berbicara melalui telepon dengan 21 orang tua dan anak-anak dari 15 keluarga di Gaza antara bulan Januari dan April. Meskipun setiap situasi bersifat unik, baik pria, wanita, dan anak-anak menggambarkan pengalaman yang sangat mirip, yaitu perang yang menimbulkan dampak buruk terhadap orang yang mereka cintai dan kesehatan mental mereka.
“Perasaan tidak berdaya membunuh ibu dan ayah,” kata Muhammad al-Nabahin, ayah empat anak dari kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah.
The Post telah membuat sketsa untuk menggambarkan kata-kata anak-anak tersebut, karena dalam banyak kasus keluarga kehilangan ponsel mereka atau tidak dapat berbagi foto karena masalah konektivitas.
Nabahin dan orang tua lainnya mengatakan bahwa mereka sangat menyadari bahwa upaya mereka untuk melindungi keluarga mereka akan sia-sia – bahwa tidak makan tidak akan melindungi anak-anak mereka dari kelaparan, bahwa mengikuti perintah evakuasi tidak akan menjamin keselamatan mereka.
Perang dimulai pada 7 Oktober, ketika pejuang Hamas menyerang komunitas di Israel selatan dan menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk keluarga yang tertidur di tempat tidur mereka. Setidaknya 36 orang yang tewas adalah anak-anak. Israel mulai membom Gaza dalam beberapa jam; sekarang, sebagian besar wilayah Jalur Gaza hancur.
Diperkirakan 29.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak
Dari lebih dari 34.000 warga Palestina yang terbunuh, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Pasukan Pertahanan Israel mengatakan bahwa mereka berupaya melindungi warga sipil, dan Hamas menggunakan mereka sebagai tameng manusia.
Sekitar 1,7 juta warga Palestina, sekitar 850.000 di antaranya adalah anak-anak, telah meninggalkan rumah mereka, menurut UNICEF – sebagian besar berjalan kaki, membawa ransel dan ransel yang diisi dengan tergesa-gesa.
Nabahin mengatakan keluarganya nyaris tidak selamat dari serangan di dekat rumah mereka di kamp Bureij pada minggu-minggu awal perang. Namun saat mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang terus ditanyakan keempat anaknya adalah mainan yang mereka tinggalkan.
Selama jeda pertempuran selama seminggu pada akhir November, Nabahin setuju untuk membawa pulang anak-anaknya, untuk memulihkan apa pun yang mereka bisa. Tapi semuanya “hancur,” katanya. “Mereka mulai menangis.”
Ahmed, putranya yang berusia 13 tahun, mengatakan kepada The Post: “Saya tidak percaya bahwa saya belum mati.”
“Aku kehilangan semua temanku, keluargaku, dan rumahku. Saya melihat kematian dengan mata kepala saya sendiri. Saya ditarik dari bawah reruntuhan. Yang kukatakan pada orang tuaku hanyalah aku ingin hidup. Saya tidak suka kematian.”
— Ahmed Abu Lebda, 13 tahun

Nabahin menggambarkan rasa malu yang merasuki dirinya saat Ahmed berbicara. “Saya tidak punya apa-apa selain lengan saya untuk menyembunyikan mereka dari kematian,” katanya. Putrinya, Tala, meminta hadiah ketika dia berusia 10 tahun pada bulan Desember, namun keluarganya hampir tidak mampu membeli makanan untuk hari itu.
Bagi sebagian besar anak-anak Gaza, ini bukanlah perang pertama mereka. Mereka yang berusia di bawah 18 tahun telah selamat dari setidaknya empat putaran konflik sebelumnya. Kebanyakan dari mereka tidak pernah meninggalkan daerah kantong yang diblokade tersebut. Namun orang tua mereka mencoba membangun dunia yang berbeda untuk mereka.
Penulis Rasha Farhat, 47, mengajari keempat anaknya tentang budaya Palestina dan keindahan Gaza, katanya. Mereka membaca buku bersama, lalu menjelajahi perpustakaan umum untuk mencari informasi lebih lanjut. Berwisata ke pantai memberi mereka waktu untuk bernapas, kata Farhat.
Keluarga tersebut meninggalkan Kota Gaza menuju Khan Younis pada 14 Oktober, berharap kota di Gaza selatan akan lebih aman. Rasanya tidak terlalu lama. Kini di Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Gaza berlindung di sepanjang perbatasan Mesir, mereka tinggal di antara orang-orang yang hampir tidak mereka kenal. Untuk sesaat, gadis-gadis itu bertanya mengapa mereka tidak bisa pulang. Mereka berhenti ketika seorang tetangga memberi tahu bahwa rumah mereka telah hilang.
Habiba, 10 tahun, masih berharap dia membawa lebih banyak pakaian dan mainan.
“Saya sedang berbicara dengan Anda sekarang dan saya takut,” kata Farhat. “Saya mencoba menyembunyikannya dari anak-anak saya, tetapi mereka menyadari rasa takutnya.”
“Saya berusaha menjadi kuat,” katanya, namun dia takut tubuhnya mengkhianatinya. Dia sedang menurunkan berat badan. “Terkadang kami tertawa histeris. … Di lain waktu kita kehilangan kendali dan menangis.”
Dengan Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, dan kekacauan yang menghambat distribusi pasokan yang tiba, 95 persen orang di Jalur Gaza menghadapi “krisis kelaparan” pada bulan Maret, menurut a Laporan yang didukung PBB. Di wilayah utara yang hancur, kata UNICEF1 dari 3 anak di bawah usia 2 tahun mengalami kekurangan gizi akut.
“Kematian anak-anak yang kami khawatirkan telah terjadi dan kemungkinan akan meningkat pesat kecuali perang berakhir,” Adele Khodr, kata direktur regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, pada awal Maret. Pada awal April, otoritas kesehatan setempat mengatakan, 28 anak meninggal karena kekurangan gizi atau komplikasi terkait dehidrasi.
Para orang tua “bangun dan kemudian mereka harus memutuskan: “Apakah Anda mengantri untuk mendapatkan roti selama enam jam atau Anda ingin tetap tinggal dan menjaga keutuhan keluarga,” kata Janti Soeripto, CEO dan presiden Save the Children.
Safia Abu Haben, nenek 12 anak dari kamp pengungsi Jabalya di Gaza utara yang kini tinggal di tenda di Rafah, mencoba menciptakan momen pelepasan bagi anak-anak tersebut. Dia bercerita kepada mereka. Dia terus memeriksa krayon di supermarket agar bisa menggambar, tapi tidak ada lagi krayon seperti itu di rak.
Mayar, cucunya yang berusia 12 tahun, sedang berjuang untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya: “Saya merasa aneh di tempat ini,” katanya. “Tempat ini sama sekali bukan milikku.”
“Saya melihat mayat dan orang mati ketika rumah kami dibom pada awal perang. Kapan saya akan kembali ke rumah saya? Ibu saya memberi tahu saya bahwa kami akan segera kembali, tetapi saya tidak mempercayainya karena misil tidak berhenti dan segala sesuatu di sekitar saya mengatakan bahwa kami tidak akan kembali.”
— Mayar Abu Haben, 12 years old

Di sebuah tenda di dekatnya, Muhammad al-Arair, 33, sedang mencari, namun tidak berhasil, seorang psikolog yang dapat menghilangkan teror malam yang dialami anak-anaknya.
“Saya menarik anak-anak saya keluar dari reruntuhan, dan mereka sekarang menderita gangguan stres pascatrauma,” katanya. “Mereka berteriak sepanjang malam. Mereka terus-menerus merasa bahwa mereka masih berada di bawah reruntuhan.”
Beberapa orang tua khawatir mereka akan kehilangan anak-anak mereka karena dunia pribadi yang berada di luar jangkauan mereka. Anak-anak yang dulunya selalu ngobrol akan diam dan menyendiri. Mereka mempunyai pemikiran yang tidak akan mereka bagikan.
Nawal Natat, 47, mengatakan putri remajanya mulai buang air kecil tanpa sadar. Tinggal di halaman sekolah perempuan di Rafah, dikelilingi orang-orang asing, ia hanya ingin sendiri, mengabaikan kakak-kakaknya dan hiruk-pikuk di sekitarnya. Natat tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya.
“Dia malu,” kata Natat. “Kenyataannya pahit dan di luar kendali saya.”
Mahmoud al-Sharqawi, 34, mengatakan dialah yang menarik diri dari ketiga anaknya yang masih kecil, takut dengan pertanyaan mereka dan malu karena ketidakmampuannya menafkahi mereka. “Sebelumnya, saya sangat dekat dengan mereka – kami berteman,” katanya. “Hati saya sakit saat mereka terendam air hujan dan anggota tubuh mereka menggigil. Saya tidak bisa memberi mereka kehangatan.”
Perang telah meracuni mimpi apa pun yang pernah ia alami. “Saya dulu membayangkan putri saya Tala sebagai seorang insinyur, Yasser sebagai pengacara, dan Zaina sebagai dokter. Sekarang saya hanya membayangkan mereka di jalan.”
Keluarga-keluarga yang mengungsi jauh dari dokter yang biasa mereka gunakan, dan seringkali tidak ada pengobatan yang tersedia untuk anak-anak dengan kondisi kesehatan jangka panjang. Israel telah menargetkan banyak rumah sakit di daerah kantong tersebut, dengan tuduhan bahwa rumah sakit tersebut digunakan oleh militan, dan membuat sistem layanan kesehatan yang sudah lemah menjadi lumpuh.
Heba Hindawi, 29, mengatakan putrinya yang berusia 10 tahun, Amal, dilahirkan dengan lubang di jantungnya, sehingga dia berisiko lebih besar terkena serangan jantung atau stroke. Ketika mereka mendengar pesawat tempur, Amal akan memberi tahu Hindawi bahwa menurutnya jantungnya akan berhenti berdetak jika bom mendarat terlalu dekat; ibu tiga anak ini akan memeluk anaknya dan meyakinkannya bahwa dia aman.
“Aku mengatakan ini padanya,” kata Heba, “tapi aku yakin jantungnya mungkin akan berhenti berdetak.”
Berkumpul bersama orang tua dan saudara-saudaranya di dalam tenda, Amal hanya berharap dirinya hangat.
“Hujan dan hawa dingin yang menggigit menggerogoti hatiku yang lelah. Kami tidak tidur semenit pun tadi malam karena hujan deras.”
— Amal Hindawi, 10 tahun

Menjelang musim panas, pekerja bantuan mulai khawatir akan dampak kenaikan suhu. Philippe Lazzarini, komisaris jenderal badan PBB untuk pengungsi Palestina, dikatakan setidaknya dua anak baru-baru ini meninggal karena panas.
Israel kini mengancam akan menyerang Rafah, yang menurut mereka merupakan benteng terakhir Hamas – namun juga merupakan tempat perlindungan terakhir bagi banyak keluarga Palestina.
Natat sudah kehabisan cara untuk menjelaskan kepada anak-anaknya apa yang terjadi pada mereka – tidak ada pembenaran yang masuk akal, katanya. “Mereka bertanya kepada saya mengapa kita hanya menghadapi hal ini di Gaza,” katanya. “Mereka selalu mengatakan kepada saya bahwa mereka seharusnya mempunyai hak untuk hidup seperti anak-anak di seluruh dunia.”
Bagi Nabila Shinar, 51 tahun, satu-satunya cara menghilangkan rasa takutnya adalah dengan jujur kepada anak-anaknya. “Tidak dapat disangkal adanya kerugian bagi mereka,” katanya. “Saya mencoba membuat mereka lebih berani.”
Putranya Yazan, 14, dihantui oleh apa yang dilihatnya di jalan selatan. Namun, dia mencoba menyingkirkan gambaran itu. Dia merasa seperti orang dewasa sekarang.
“Saya melihat wanita yang dibunuh dan anak-anak mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa mereka yang mengalami pendarahan. Aku masih merasakan penyesalan dan kesakitan atas apa yang kulihat, tapi ibuku memberitahuku bahwa semua ini akan segera berakhir, dan aku percaya pada ibuku.”
— Yazan Shinar, 14 tahun

Tentang cerita ini
Ilustrasi oleh Ghazal Fatollahi. Desain dan pengembangan oleh Brandon Ferrill.
Harb melaporkan dari London. Claire Parker di Kairo berkontribusi pada laporan ini.
Penyuntingan oleh Reem Akkad, Jesse Mesner-Hage dan Joseph Moore. Penyuntingan salinan oleh Martha Murdock.